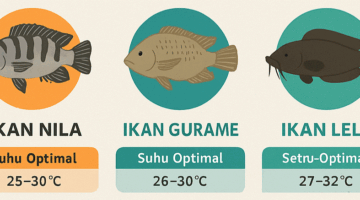Malam itu hujan turun tanpa jeda di Dataran Tinggi Dieng. Angin dingin menyapu lembah, menyusup di antara ladang kentang dan rumah-rumah sederhana di Dukuh Legetang, Desa Pekasiran, Kecamatan Batur. Tak ada yang menyangka, malam 16 April 1955 menjadi malam terakhir bagi ratusan jiwa.
Sekitar pukul 23.00 WIB, suara gemuruh terdengar memecah kesunyian. Dari kejauhan, bunyinya seperti gunung runtuh. Warga di desa sekitar mendengarnya, tetapi gelap, hujan lebat, dan medan berat membuat tak seorang pun berani mendekat.
Pagi harinya, Dukuh Legetang telah lenyap.
Tak tersisa rumah, jalan, apalagi kehidupan. Seluruh kawasan berubah menjadi gundukan tanah raksasa. Dukuh yang semula berada di sebuah lembah itu kini menjelma seperti bukit baru—mengubur penghuninya hidup-hidup.
Material longsor raksasa yang dipicu runtuhnya lereng Gunung Pengamun-amun menimbun dukuh tersebut. Sekitar 351 orang meninggal dunia, menjadikannya salah satu bencana longsor paling mematikan dalam sejarah Indonesia.
Dukuh Subur di Atas Tanah Rawan
Sebelum tragedi, Legetang dikenal sebagai wilayah yang subur. Tanah vulkanik Dieng menjadikan kawasan ini cocok untuk pertanian. Sebagian besar warga menggantungkan hidup pada hasil kebun.
Lanskapnya indah. Udara sejuk. Kehidupan berjalan sederhana.
Namun di balik kesuburan itu, tersimpan kerentanan geologis:
- Struktur tanah vulkanik yang gembur
- Kemiringan lereng yang curam
- Curah hujan tinggi khas pegunungan
Kombinasi inilah yang kemudian menjadi pemicu bencana besar.
Dalam perspektif kebencanaan modern, peristiwa Legetang adalah longsor akibat kejenuhan air dalam tanah yang menyebabkan lereng kehilangan daya ikatnya.
Longsor yang Mengubur Satu Dukuh Sekaligus
Yang membuat tragedi ini begitu menggetarkan adalah skalanya.
Longsor tidak sekadar menghantam sebagian wilayah, tetapi langsung menimbun seluruh permukiman. Dalam hitungan menit, satu dukuh hilang dari peta.
Kesaksian warga sekitar menyebut:
- Tidak ada tanda-tanda awal yang jelas
- Tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri
- Tidak terdengar teriakan karena semua terjadi sangat cepat
Hanya satu-dua kisah tentang kemungkinan korban selamat yang beredar, tetapi hingga kini tetap simpang siur.
Tugu Sunyi Penanda Duka
Kini, di lokasi tersebut berdiri sebuah tugu peringatan.
Tulisan pada lempeng logamnya menjadi saksi bisu:
“Tugu peringatan atas tewasnja 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornja Gunung Pengamun-amun pada tg. 16/17-4-1955.”
Tugu itu bukan sekadar monumen, melainkan pengikat memori kolektif masyarakat Dieng tentang duka yang tak pernah benar-benar usai.
Dari Bencana Alam ke Narasi “Dukuh Sodom”
Seiring waktu, tragedi ini tidak hanya dikenang sebagai bencana alam.
Muncul cerita yang menyebut Legetang sebagai “Dukuh Sodom”—sebuah istilah yang merujuk pada kisah kaum Nabi Luth dalam tradisi Islam maupun kota Sodom dan Gomora dalam tradisi Alkitab.
Cerita yang beredar dari mulut ke mulut menyebut:
- Maraknya perjudian
- Praktik prostitusi
- Tarian erotis pada malam hari
- Penyimpangan seksual
- Mushala yang disebut tak lagi difungsikan sebagaimana mestinya
Narasi ini kemudian berkembang menjadi keyakinan bahwa longsor tersebut adalah azab.
Namun secara historis dan akademis, kisah tersebut tidak memiliki bukti faktual yang dapat diverifikasi. Ia hidup sebagai bagian dari folklor dan cara masyarakat memaknai tragedi.
Fenomena seperti ini tidak unik di Dieng. Dalam banyak peristiwa bencana besar, masyarakat kerap membangun penjelasan moral atau religius sebagai bentuk refleksi kolektif.
Antara Mitos, Trauma, dan Penguatan Religiusitas
Pasca tragedi Legetang, kehidupan masyarakat Pekasiran berubah.
Trauma mendalam membuat masyarakat:
- Lebih religius
- Menghindari perilaku yang dianggap menyimpang
- Menjadikan tragedi sebagai pelajaran moral
Dengan demikian, narasi “azab” lebih berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk membangun tatanan nilai baru.
Disandingkan dengan Pompeii
Tragedi Legetang kerap dibandingkan dengan kehancuran:
- Pompeii
yang musnah akibat letusan - Gunung Vesuvius
Kesamaannya terletak pada:
- Kehancuran mendadak
- Permukiman yang terkubur
- Membeku dalam memori sejarah
Bedanya, Legetang nyaris tak menyisakan artefak kehidupan karena tertimbun tanah longsor.
Pelajaran Kebencanaan untuk Masa Kini
Lebih dari sekadar kisah kelam, tragedi ini menyimpan pesan penting:
Dieng adalah kawasan rawan longsor.
Peristiwa Legetang menjadi pengingat bahwa:
- Pemukiman di lereng harus memperhatikan aspek geologi
- Curah hujan ekstrem perlu diwaspadai
- Mitigasi bencana adalah kebutuhan mutlak
Jejak yang Tak Pernah Hilang
Hari ini, tak ada lagi Dukuh Legetang.
Yang tersisa hanya bukit sunyi, tugu peringatan, dan cerita yang terus diwariskan.
Namun bagi masyarakat Dieng, Legetang bukan sekadar lokasi bencana. Ia adalah:
- Luka sejarah
- Pengingat spiritual
- Pelajaran tentang alam dan kehidupan
Sebuah desa yang hilang dalam semalam—tetapi tak pernah benar-benar hilang dari ingatan.
Penutup
Tragedi Dukuh Legetang adalah pertemuan antara fakta geologi, memori kolektif, dan konstruksi budaya masyarakat.
Di balik narasi “Dukuh Sodom”, terdapat realitas tentang rapuhnya manusia di hadapan alam.
Dan di atas bukit yang sunyi itu, sejarah terus berbisik:
bahwa bencana bukan untuk ditakuti semata, melainkan untuk dipahami dan diantisipasi.